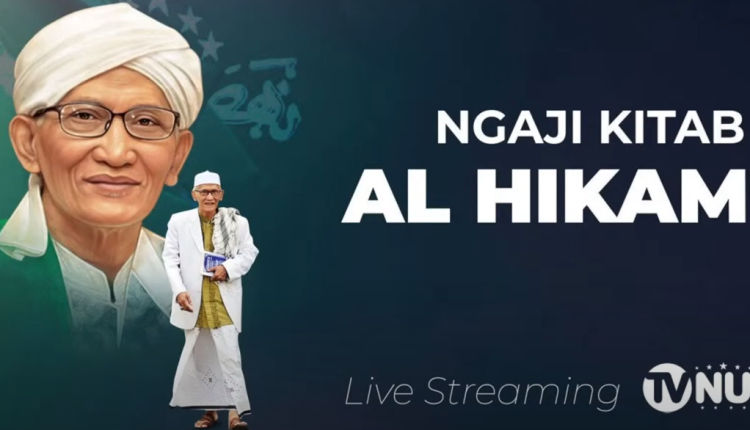Syaikh Ibnu Athâillâh al-Sakandari berkata: “al-Nûr lahû al-Kasyfu, wa al-Bashîrah lahâ al-Hukmu, wa al-Qalbu lahâ al-Iqbâl wa al-Idbâr”. Secara sederhana pernyataan al-Sakandari ini dapat kita pahami bahwa cahaya memiliki fungsi untuk mengungkap, bashîrah (mata hati) memiliki fungsi untuk menilai, dan kalbu memiliki kecenderungan untuk mendekat atau menjauh. Dalam tradisi tasawuf, ada ungkapan bahwa kalimat yang ditulis oleh seorang bijak bestari, apalagi jika menggunakan bahasa Arab, kadang memiliki dua makna, yakni majazi dan hakiki. Majazi sendiri merupakan istilah dalam kesusasteraan Indonesia yang memiliki arti kiasan untuk menciptakan keindahan kata dengan makna yang lebih dalam. Sedangkan ungkapan hakiki adalah kalimat yang memiliki makna dasar tanpa kiasan tertentu sehingga maknanya mampu dipahami oleh kebanyakan orang.
Ungkapan al-Sakandari di atas apabila dilihat dari kacamatan sastra, merupakan ungkapan yang sarat akan makna majazi. Sehingga dalam hal ini, Ibnu Abbad al-Nafari, pensyarah kitab al-Hikam yang kita kaji ini memberikan komentar yang cukup holistik terhadap ungkapan al-Sakandari di atas. Menurut Ibnu Abbad, ungkapan al-Sakandari adalah lafadz yang bermacam-macam dengan aneka makna yang beragam. Dalam hal ini, cahaya atau nur berfungsi untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi sehingga menjadi jelas dan terlihat. Lalu kemudian, bashîrah (mata hati) berfungsi untuk menilai, memastikan kebenaran dari apa yang telah disaksikannya. Sedangkan kalbu memiliki kecenderungan untuk mendekat (al-Iqbâl), yaitu ia bertindak sesuai dengan apa yang disaksikan oleh mata hati, dan juga memiliki kecenderungan untuk menjauh (al-Idbâr), yaitu meninggalkan sesuatu sesuai dengan apa yang disaksikan oleh bashîrah.
Dalam kajian ini, nur pengertiannya tidak hanya sebatas cahaya dalam artian yang sempit. Dalam literatur tasawuf, nur seringkali dipahami dengan pengetahuan dan pencerahan yang mampu membimbing manusia keluar dari kegelapan kebodohan yang mencekam. Senada dengan ini, al-Ghazali menegaskan bahwa nur merupakan simbol pengetahuan dan kebenaran dengan cara menerangi akal dan kalbu manusia, sehingga mereka mampu memahami hakikat-hakikat yang tersembunyi. Karena itulah dalam spektrum tasawuf, al-Ghazali lalu membagi nur dalam arti pengetahuan, ke dalam tiga diversifikasi, yaitu (1) al-Nûr al-Hissî, atau pengetahuan indrawi, (2) al-Nûr al-Ma’nawî atu pengetahuan akal, dan (3) al-Nûr al-Qalbî atau pengetahuan kalbu. Dari ketiga diversifikasi nur ini, sejatinya nur yang paling tinggi adalah al-Nûr al-Qalbî karena ia mampu menembus sekat-sekat dimensi alam materi duniawi menuju dimensi ukhrawi, hingga Arasy.
Secara bahasa, Bashîrah bermakna mata hati atau pengelihatan batin. Ia adalah anugerah yang Allah berikan kepada para hamba yang dekat dengan-Nya. Meskipun berasal dari kata yang yang sama, “Bashîrah”, berbeda dengan “Basharun” yang bermakna pengelihatan fisik. Dengan kata lain, pengelihatan batin lebih canggih daripada pengelihatan fisik, karena Bashîrah mampu melihat kebenaran, hakikat, dan makna di balik sesuatu yang tak mampu dilihat oleh Basharun. Contoh sederhana yang bisa kita ambil dari kecanggihan bashîrah adalah kemampun seseorang dalam melihat ketidak-baikan orang lain yang terpatri dalam hatinya, meskipun secara zahir dibungkus dengan penampilan baik. Dalam pengelihatan fisik, penampilan zahir menjadi acuan dalam menilai seseorang, namun hal itu tidak cukup untuk menjamin hatinya juga ikut baik. Karena itulah, kita sering mendengar istilah “Don’t judge a book by its cover” yang artinya: Jangan menilai sebuah buku hanya dari kovernya.
Pesan di atas apabila dipahami secara mendalam mengajarkan kepada kita bahwa pengelihatan fisik seringkali ditipu oleh manipulasi-manipulasi semu yang berdampak pada subjektivitas penilaian. Tanpa melibatkan bashîrah dalam melihat seseorang, kita akan terjerembab pada penilaian subjektif yang sifatnya bias dan cenderung tidak adil. Akibatnya, orang yang secara fisik tidak baik dianggap tidak benar karena penampilannya yang tak sesuai dengan ekspektasi. Sebaliknya, orang yang berhati busuk dianggap sebagai orang baik, hanya karena penampilannya yang cukup modis dan parlente. Dari uraian ini jelas bahwa dampak dari subjektivitas penilaian terhadap orang lain itu lahir karena kita tidak adil sejak dalam pikiran. Ketidak-adilan itu muncul karena kita hanya fokus pada pendekatan pengelihatan fisik daripada pengelihatan batin. Dengan demikian dalam melihat seseorang, idealnya adalah menempatkan konsep basharun dan bashîrah dalam satu piranti yang utuh agar tidak terjadi bias penilaian dan ambiguitas pandangan.
Berbicara tentang kalbu, maka kita akan disuguhkan ke dalam dua pengertian umum, yaitu kalbu sebagai organ tubuh manusia berupa segumpal daging. Dalam istilah medis, pengertian kalbu seperti ini dikenal dengan jantung, ada juga yang menyebutnya dengan lever atau hati. Pengertian selanjutnya adalah kalbu yang oleh al-Ghazali diistilahkan dengan “Lathîfah Rabbâniyyah wa Rûhâniyyah” atau sesuatu yang bersifat transenden dan spiritual. Peran kalbu pada diri manusia sangat penting, karena ia menjadi pembeda antara dirinya dengan makhluk lain. Para bijak bestari seringkali membuat diksi menarik mengenai hal itu, salah satu contohnya adalah “al-Insânu Hayawân Nâthiq”, manusia adalah makhluk hidup yang berlogika. Jika mengacu pada konsep kalbu sebagaimana disebut oleh al-Ghazali dengan “Lathîfah Rabbâniyyah”, maka pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, berlogika, dan berpengetahuan.
Itulah yang kemudian membedakan antara manusia itu sendiri dengan makhluk lainnya, karena dalam sejarah, manusialah satu-satunya makhluk yang mampu bertahan serta mampu membuat peradaban di muka bumi, karena potensi kalbu tersebut. Sedangkan makhluk lain, seperti hewan misalnya, ia hanya mempunyai insting atau gharîzah, namun tidak mempunyai kalbu. Lewat kalbu ini pula, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kalbu yang tersemat pada diri manusia mampu melahirkan kehendak dalam memilah dan memilih, atau mendekat dan menjauh terhadap sesuatu yang punya konsekuensi terhadap dirinya. Kalbu yang bersih yang senantiasa bersambung kepada Allah s.w.t. mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Karena itu, sebagai tempat bersemayamnya cahaya ilahi, kalbu menjadi pusat segala aktivitas manusia, baik lahir maupun batin. Ia jadi penentu arah ke mana manusia hendak berlabuh dalam hidupnya, sekaligui penentu kualitas hidupnya. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda: “Inna fî al-Jasadi Mudghatun, Idzâ Shalahat Shalaha al-Jasadu Kulluhû, wa Idzâ Fasadat Fasada al-Jasadu Kulluhû, Alâ wa Hiya al-Qalbu”. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah kalbu. Wallâhu A’lam bis Shawâb
(Transkip pengajian Syarah Hikam oleh Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar pertemuan ke-85 live di TVNU).